Minggu ini, publik kita dimeriahkan oleh kontroversi mengenai aturan untuk tidak mengenakan kerudung di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Alasannya, pertama, kerudung membuat mahasiswa tidak dapat diidentifikasi dan mengganggu komunikasi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kedua, diduga bahwa kerudung lebih ideologis (radikal) daripada fiqh. Karena itu, mereka yang berkerudung akan dibina oleh kampus.
Tentu saja ada pro, ada pula yang kontra. Pro, setuju dengan alasan itu. Sedangkan kontra menganggap aturan melanggar hak perempuan untuk memilih pakaian mereka sendiri, melanggar kebebasan perempuan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka dalam interpretasi mereka tentang keragaman yang menilai kerudung sebagai sesuatu yang wajib atau setidaknya diperlukan untuk seorang wanita Muslim. Adapun identifikasi dan komunikasi, itu adalah masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan lebih elegan.
Pada dasarnya, kerudung itu bebas nilai. Jadi, tidak perlu dihukum. Karena itu, jika ada kecenderungan ideologis pada orang yang memakainya, yang perlu ditangani adalah tindakan ideologis yang tidak pantas atau berbahaya, bukan jilbab. Daripada melarangnya, apalagi dilakukan oleh lembaga pendidikan, lebih baik mendidiknya hanya agar tabir dilepaskan dengan kesadaran, bukan paksaan.
Terlepas dari huru-hara, menarik untuk membahas Islam dan budaya dalam konteks lembaran.
Islam tidak ada untuk menghilangkan apa pun, kecuali kesengsaraan. Padahal, bertentangan dengan agama lain yang hadir sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Islam itu sempurna. Beberapa doktrin dan ritual Islam dapat ditemukan pada orang Yahudi dan Kristen. Termasuk penggunaan kerudung yang jejaknya ada di orang Yahudi.
Terutama di samping agama, misalnya budaya. Apa yang diperangi Nabi Muhammad adalah ketidaktahuan tradisi Arab pada waktu itu. Adapun budaya positif, itu dilestarikan dengan menyempurnakan konten nilai-nilai Islam. Paradigma Nabi kemudian dipegang teguh oleh pengkhotbah Islam pertama di nusantara: toleran terhadap agama lain, akulturasi dengan budaya nusantara, dan terbuka terhadap berbagai nilai kebaikan dari mana pun ia datang (meskipun dari mulut seorang munafik) , kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib).
Jadi, dalam semangat Islam yang memiliki budaya nusantara, dalam konteks jilbab, itu bahkan lebih konkret, mendasar, dan tidak dicurigai jika upaya dikembangkan untuk melihat jilbab dalam konteks hubungan Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai budaya. Karena memang budaya memiliki ruang besar dalam pertimbangan hukum (fiqh).
Kerudung tentu bukan budaya kita. Karena itu, jika bukan masalah di Saudi karena memang ada basis budaya, itu berbeda dengan Indonesia.
Secara doktrin, hukum kerudung masih sangat terbuka untuk diperdebatkan. Secara yuridis, masih bisa diperdebatkan karena mayoritas sarjana tidak menganggapnya sebagai kewajiban. Dalam arti tertentu, wajah seorang wanita Muslim bukanlah aurat.
Di sisi lain, ada budaya Indonesia yang tidak memiliki jejak kerudung. Jadi, yang benar-benar signifikan adalah studi fiqh yang disintesis dengan budaya terkait jilbab sehingga dapat melahirkan formulasi hukum yang membuat wanita Muslim bisa memahami mengapa jilbab tidak boleh digunakan oleh wanita Muslim Indonesia. Itu sebenarnya lebih strategis dan efektif untuk organisasi Islam dan lembaga pendidikan Islam.
Budaya yang juga perlu diperhatikan adalah budaya saat ini di mana wajah menjadi salah satu identitas di berbagai negara. Terutama negara-negara Eropa.
Selain itu, persepsi masyarakat (tumpang tindih di negara-negara non-Muslim) yang cenderung negatif terhadap jilbab juga perlu dipertimbangkan dalam penarikan hukum (fiqh). Karena, bagaimanapun, selama ada alternatif hukum, persepsi orang yang dapat menyebabkan fitnah adalah sesuatu yang juga dipertimbangkan dalam Islam.
Tanpa pendekatan ini, ketidakterizinan jilbab hanya akan memicu kecurigaan dan pertentangan, termasuk mereka yang tidak berkerudung.
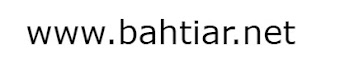











0 Comments