Munculnya Islamisme global dalam bentuk al-Qaeda dan Negara Islam Irak dan al-Sham ( ISIS) telah menjadi tantangan besar bagi keamanan negara-negara Barat dan mayoritas Muslim selama bertahun-tahun yang akan datang. Ancaman ini sangat menakutkan di negara-negara Muslim karena klaim Islamisme sendiri bahwa itu mewakili Islam dalam bentuk yang paling murni dan paling benar menurut mereka. Yang perlu dicatat, kekuatan dan daya tarik gerakan Islamis juga berasal dari kemampuan mereka untuk mengklaim bahwa ini akan memajukan keadilan dan kebebasan - tujuan politik yang mayoritas umat Muslim inginkan secara alami. Banyak Islamis dapat membenarkan perjuangan mereka dan kekerasan mereka dengan menghadirkan beberapa agenda sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk reformasi sosial dan politik. Masyarakat Muslim saat ini tengah menghadapi reruntuhan ideologis; mereka sangat membutuhkan gerakan agenda reformasi yang konsisten dengan tradisi iman yang sebenarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pencarian alternatif untuk Islamisme telah digagalkan oleh konflik sektarian yang meluas dalam Islam, yang telah meningkatkan ketegangan dan mendorong kekerasan di seluruh dunia. Mengingat keadaan darurat ini, kebutuhan untuk mereformasi yurisprudensi Islam dan pemikiran sosial telah menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Ancaman Islamisme terhadap Muslim itu sendiri, bagaimanapun, telah diperparah oleh melemahnya pemikiran kritis dalam tradisi agama dan politik Islam. Dalam mengembangkan alternatif reformis terhadap Islamisme itu sendiri, umat Islam memang memiliki tubuh substansial dari pemikiran historis maupun kontemporer yang dapat mereka manfaatkan untuk membantu memperbaiki struktur politik dan sosial guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Pandangan umum yang disebarkan oleh kelompok Islamis dari semua varietas hukum Syariah “secara ilahiah sudah ditakdirkan” dan tidak dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, syariah harus dipahami secara harfiah, dan Islamis didorong oleh keyakinan mereka bahwa Syariah merupakan sistem politik dan kepercayaan yang komprehensif. Islamis harus melihat Syariah sebagai satu-satunya sumber politik dan pemerintahan yang sah; akibatnya, mereka percaya bahwa Syariah harus ditegakkan di seluruh dunia oleh negara Islam yang kuat dan luas. Dalam mencapai tujuan ini, kaum Islamis telah mengejar tujuan-tujuan politik transisional melalui berbagai cara, termasuk proselitisasi dan perjuangan bersenjata. Fokus langsung perjuangan mereka adalah menggusur elit dan kekuatan militer yang berorientasi Barat di masyarakat Muslim, pada akhirnya, mereka akan menggulingkan apa yang mereka pandang sebagai rezim musuh yang menindas yang telah menduduki masyarakat Muslim.
Apa yang dibuktikan oleh para pembasmi abad kesembilan belas dan ahli warisnya adalah, bahwa sebagian besar aturan hukum dan striktur yang terdiri dari Syariah dikembangkan selama abad kesembilan dan kesepuluh dari Kerajaan Abbasiyah yang besar (750 H-1258 H), yakni dua abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Badan hukum tradisional ini terdiri dari pendapat hukum para ahli hukum yang menafsirkan Quran dan tradisi para nabi. Seperti semua sistem hukum dan politik buatan manusia lainnya, prinsip-prinsip dan nilai-nilai interpretasi ini tidak boleh dilihat sebagai statis tetapi sebagai dinamis dan evolusioner tergantung pada konteksnya. Akan tetapi, perlu dicatat juga bahwa pendekatan literalis terhadap Syariah pada dasarnya membekukan penafsiran yang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh sarjana Ziauddin Sardar, dominasi literalisme membuatnya dipercaya menjadi penerima pasif daripada pencari kebenaran aktif. Kenyataannya, Syariah tidak lebih dari sekumpulan prinsip, kerangka nilai, yang memberi panduan kepada masyarakat Muslim.
Pembekuan penafsiran ini telah meningkatkan Syariah secara palsu menjadi status teks ilahi. Selama berabad-abad, ini mengarah pada legitimasi - dan permintaan - sebuah literalisme yang menangguhkan agen manusia dan mengesampingkan persyaratan dunia yang terus berubah. Bersamaan dengan itu, Islam juga berbaur dengan kekuasaan negara ketika kerajaan-kerajaan Muslim berusaha melegitimasi kekuasaan mereka dengan dekrit dari ulama tradisionalis. Misalnya, ciri kode hukum sebuah konsep "kemurtadan," yang secara historis melayani untuk mencegah pemberontakan melawan negara kekaisaran. Islamis modern, baik yang terorganisir sebagai negara dalam kasus Arab Saudi, Republik Islam Iran dan Afghanistan di bawah Taliban, atau sebagai milisi dalam kasus Boko Haram di Afrika Barat, telah mengeksploitasi aspek kuno jurisprudensi tradisional islam untuk menegakkan sendiri agenda politik yang radikal.
Sepanjang sejarah Islam, para pemikir Muslim bebas mengangkat suara mereka melawan kodifikasi ketat pemikiran dan praktik Islam. Namun yang terpenting, pandangan-pandangan alternatif ini selalu menghadapi perlawanan yang kuat dan sering kali dibatalkan. Misalnya, cendekiawan dan teolog Islam Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazali (1058-1111 H) dengan keras mengkritik praktik Mu'tazilah yang menundukkan teologi Islam ke rasionalisme. Seiring waktu, peran para filsuf Muslim secara signifikan juga ikut melemahkan. Pada 1017-18 dan 1029, Khalifah Abbasiyah al-Qadir (947-1031 H) malah mengeluarkan dekrit yang dikutip secara luas yang melarang Mu'tazilitisme, dalam memadamkan perbedaan pendapat, seluruh kelompok dianiaya dan teks mereka dihancurkan. Bahkan hari ini, berabad-abad kemudian, karya-karya Ibn al-Rawandi, Ibn Rushd, dan al-Biruni - pemikir Muslim progresif dan ilmiah di zaman mereka - dilarang dari kurikulum resmi di Arab Saudi dan sebagian besar negara-negara Teluk. Sebaliknya, hanya para ulama dan sekolah yurisprudensi yang diakui resmi yang dianggap sah.
Dari berbagai mazhab pemikiran Islam, Salafisme - dan manifestasinya yang lebih kontemporer, Wahhabisme - melambangkan literalisme Salawi yang memfosil dan memperlakukan hukum buatan manusia sebagai sesuatu yang ilahi. Istilah Salafisme berasal dari al-salaf al-salih (leluhur yang saleh) maksudnya menggunakan cara Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fokus utamanya ada pada apa yang merupakan perilaku religius dan sosial Nabi. Perilaku ini disimpulkan dari Sunah (tradisi Nabi Muhammad dikompilasi dalam Hadis). Semua varian keyakinan dan praktik lainnya dianggap bid’a, atau inovasi yang tidak diinginkan.
Salafi wahabi selalu menganggap kitab suci sebagai keputusan terakhir. Sebaliknya, sekte lain dalam Islam memandang kitab suci sebagai pesan dari Tuhan yang masih membutuhkan interpretasi dan pemahaman sebelum penerapannya dalam praktik di dalam kehidupan. Para ulama Salaf mengutuk adat setempat dan praktik-praktik Muslim yang lebih mistis dari sekte-sekte seperti para Sufi, karena mereka secara sengaja merusak identitas Islam. Kutukan ini, yang dikenal sebagai takfir, adalah bagian dari doktrin radikalisme Salafi wahabi.
Pada abad kedelapan belas, Muhammad bin Abd al-Wahhab berhasil mengubah doktrin Salafi wahabi menjadi kerangka politik. Yang paling penting, perjanjiannya dengan Muhammad Ibn Saud, emir Dar'iyyah di Arabia timur laut, memberikan Wahhabisme Salafi 'kekuatan' dengan sang raja untuk pembentukan teokrasi Salafis abad kesembilan belas. Pada abad ke-20, penemuan besar minyak mempermudah komitmen Saudi untuk menyebarkan Wahhabisme ke seluruh dunia, dari Afrika Barat sampai ke Asia Tenggara. Hari ini, literalisme Salafis dan puritanisme ideologis yang didukung oleh Wahhabisme telah dianut oleh banyak Islamis, termasuk al-Qaeda dan ISIS.
Tren sejarah besar kedua yang telah melanda dunia Muslim dengan menghambat reformasi politik dan mendorong kekerasan adalah sektarianisme Sunni dan Syiah. Kebangkitan sektarianisme telah bergandengan tangan dengan dominasi literalisme Syariah. Seperti diketahui, salah satu target ideologi takfiri Salafi wahabi adalah sekte Syiah, yang menunjukkan perpecahan paling awal dalam tradisi agama. Sektarianisme modern juga didorong oleh persaingan geopolitik. Sunni Saudi Arabia dan Syiah Iran selama bertahun-tahun telah mengeksploitasi perpecahan sektarian dalam persaingan mereka untuk kepemimpinan dunia Islam. Kontes sektarian ini dimainkan setiap hari di berita utama internasional, tetapi berakar pada sejarah politik Islam.
Dalam satu abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, para pengikutnya telah membangun sebuah kerajaan yang membentang dari Eropa Spanyol ke Asia Tengah. Namun perdebatan tentang suksesi memisahkan Muslim di awal-awal kebangkitan. Kelompok dominan memilih Abu Bakr, seorang sahabat Muhamad, sebagai khalifah pertama dan menyingkirkan klaim kelompok lain yang telah mengusulkan Ali ibn Abi Thalib, sepupu Muhammad dan menantu laki-laki. Istilah Syiah berhubungan dengan shi'atu Ali, atau pengikut Ali.
Khalifah bermigrasi keluar dari Jazirah Arab dan melintasi Timur Tengah modern, pertama ke Damaskus di bawah dinasti Umayyah, dan kemudian ke Baghdad di bawah dinasti Abbasiyah. Selama berabad-abad, kekuasaan Sunni mendominasi dunia Muslim sampai dinasti Safawi yang besar di Persia yang mengadopsi Islam Syiah sebagai agama negara mereka. Orang-orang Safawi berjuang melawan khalifah Utsmaniyah untuk mendapatkan supremasi yang secara luas menetapkan garis-garis patahan geografis dan politik Timur Tengah saat ini: Syiah berada di mayoritas negara Iran, Irak, Azerbaijan, dan Bahrain; sementara itu, Sunni mendominasi di lebih dari empat puluh negara Islam dari Maroko sampai ke Indonesia.
Wahabi menilai praktik Muslim Syiah dan sistem kepercayaan mereka sebagai murtad. Ini telah diperkuat oleh perbedaan etnis antara dunia Arab (Sunni) dan Persia (Syiah). Sementara itu, retorika yang tidak manusiawi sektarian telah muncul selama berabad-abad, teknologi baru dan media sosial telah meningkatkan cakupan dan skala kritik Salafi. Islamis Sunni telah menggunakan pengaduan yang keras dan bersejarah seperti rafidha, penolak keyakinan, dan majus, Zoroaster atau crypto-Persia, untuk menggambarkan Syiah. Sementara para pemimpin Syiah dari Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, kepada para pejabat Iran secara rutin menggambarkan lawan-lawan Sunni mereka sebagai takfiri (kode untuk teroris al-Qaeda) dan Wahabi. Pada 2015, kaum fundamentalis tidak lagi harus menyusup ke masjid-masjid arus utama untuk merekrut secara diam-diam; sebagai gantinya, mereka mengklik posting blog, mereka dapat menyebarluaskan panggilan mereka untuk berjihad. Hari ini, puluhan ribu militan sektarian yang terorganisir mampu memicu konflik berskala besar di seluruh Timur Tengah.
Terlepas dari upaya banyak ulama Sunni dan Syiah, seperti Mohammad Abduh di Mesir, Mohammad Iqbal di Inggris India (modern Pakistan) dan Ali Shariati di Iran, untuk mengurangi ketegangan melalui dialog dan pemahaman, banyak ahli menyatakan keprihatinan merka, bahwa pembagian utama Islam akan menyebabkan eskalasi kekerasan. Di masa lalu, Sunni al-Qaeda dan Syiah Hizbullah mungkin tidak mendefinisikan gerakan mereka dalam istilah sektarian; sebaliknya, mereka secara tradisionalis lebih menyukai kerangka anti-imperialis, anti-Zionis dan anti-Amerika untuk menggambarkan jihad mereka dan tujuan Islamnya. Selama dekade terakhir, kedua kelompok telah bergeser dari fokus pada Barat dan Israel untuk menyerang Muslim lainnya, seperti pembunuhan al-Qaeda terhadap warga sipil Syiah di Irak dan partisipasi Hizbullah dalam perang sipil Suriah.
Hari ini, sebagai keturunan al-Qaeda, ISIS berusaha menyatukan dunia Muslim dan mengubah batas-batas geografis Timur Tengah sebelum mengubah senjatanya di Amerika Serikat dan Eropa. ISIS percaya bahwa upaya mereka yang pertama adalah harus menyingkirkan orang murtad dan Muslim "palsu", sebuah definisi yang mencakup siapa saja yang melawan mereka, bukan hanya Syiah. Muslim biasa mungkin tidak setuju dengan metode ISIS ini, dan interpretasinya tentang kekhalifahan, tetapi gagasan tentang kekhalifahan - entitas politik historis yang diatur oleh hukum dan tradisi Islam - bahkan sangat kuat di kalangan Muslim yang berpikiran lebih sekuler.
Dalam konteks Asia Selatan, barangkali pemenang terbesar pendekatan modernis untuk yurisprudensi adalah penyair dan pemikir India, Mohammed Iqbal. Menurut Iqbal, tradisional untuk inovasi hukum dalam Islam telah kalah karena ketakutan konservatif fragmentasi sosial yang diperburuk oleh rasionalisme Islam. Ketakutan ini telah menyebabkan kaum Muslim konservatif menggunakan pemahaman Syaria yang semakin sistematis dan puritan. Dengan menolak penggunaan nalar dalam menafsirkan Syariah berdasarkan konteks yang berubah, Iqbal berpendapat bahwa "massa yang tidak berpikir" akan ditinggalkan oleh para elit Muslim di "tangan-tangan intelektual" bahwa ini memaksa mereka untuk mematuhi "secara membabi buta" aturan sekolah-sekolah yang paling dominan.
Iqbal berpendapat bahwa umat Islam harus dibebaskan dari cengkeraman para teolog dan ahli hukum primitif. “Seluruh masyarakat,” tulisnya, “membutuhkan perombakan menyeluruh terhadap mentalitasnya yang sekarang agar dapat kembali merasakan keinginan dan cita-cita segar.” Menurut Iqbal, Al-Qur'an dimaksudkan untuk “membangkitkan manusia akan kesadaran yang lebih tinggi dari hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta” guna meletakkan prinsip-prinsip hukum umum dan aturan untuk perilaku manusia (khususnya, sehubungan dengan kehidupan keluarga). Karena ajaran seorang nabi berhubungan dengan "kebiasaan, cara, dan kekhasan orang-orang yang mencintainya "pendekatan terbaik untuk politik adalah memilih kelompok orang sebagai inti pusat untuk melembagakan "Syariah universal" yang berbasis konsensus.” Dengan kata lain, hukum dan praktik Islam harus mencerminkan universalitasnya dan tetap selaras dengan waktu mengedepankan prinsip pemikiran evolusi dalam Al Qur'an. Sebagai hasilnya, menurut Iqbal, “Al-Quran mengajarkan bahwa hidup adalah proses penciptaan progresif yang mengharuskan setiap generasi, dibimbing tetapi tidak terhalang oleh karya para pendahulunya, harus diizinkan untuk memecahkan masalahnya sendiri.”
Ajaran Iqbal didasarkan pada prinsip Islam ijma, atau konsensus, yang merupakan sumber utama yurisprudensi Alquran. Iqbal berpendapat bahwa secara historis prinsip konsensus ini tidak pernah mengambil bentuk kelembagaan karena itu akan menggerogoti otoritas kekaisaran khalifah. Dengan munculnya republik Muslim nasionalis dan pembentukan lembaga legislatif di negara-negara Islam, Iqbal berpendapat bahwa sudah waktunya ijma bangkit sebagai prinsip politik modern Muslim.
Selain itu, dalam pandangan dunia Iqbal, Al-Qur'an menegaskan "struktur Islam," ijtihad, atau penalaran independen, adalah cara perubahan. Ijtihad dapat dilakukan "dengan maksud untuk membentuk penilaian independen atas pertanyaan hukum" yang didasarkan pada Quran dan Hadits. Pada awalnya, penyebaran Islam dan pembentukan tatanan politik Muslim mengharuskan "pemikiran hukum sistematis" dan "dokter hukum awal," diwujudkan melalui berbagai aliran yurisprudensi Islam. Pada awal abad ke-20, bagaimanapun, Iqbal bertanya-tanya apakah dalam hukum Islam ada prospek untuk "interpretasi segar dari prinsip-prinsipnya" karena tidak inheren "stasioner dan tidak mampu melakukan pembangunan."
Selain Iqbal, sarjana Iran yang berpengaruh Ali Syariati juga menekankan bahwa Islam membutuhkan gerakan pencerahan untuk membimbing orang dan membawa dinamisme baru kepada iman. Pandangan Syariati adalah bahwa "Protestanisme Islam" diperlukan untuk kemajuan agama dan kemajuan dalam pemikiran hukumnya. Protestanisme Islam akan memungkinkan agama untuk menumpahkan faktor-faktor yang merosot yang telah melemahkan pemikirannya. Shariati berpendapat bahwa pesan-pesan agama yang ditawarkan oleh lembaga agama formal dan tradisional sudah ketinggalan zaman. Dia menyatakan bahwa hubungan antara [pendeta] dan orang-orang harus seperti hubungan antara guru dan murid - bukan antara pemimpin dan pengikut, bukan antara ikon dan peniru; orang-orang bukanlah monyet yang hanya meniru. Ide-idenya mengilhami revolusi Iran tetapi para teokrat menyesuaikan ide-idenya untuk tujuan mereka sendiri. Pesan penting Syariati tentang membebaskan Islam dari para ulama dan pemikiran-pemikiran yang ketinggalan jaman melalui nalar cukup ironis untuk dilewati dan ditumbangkan.
Pembaru abad kesembilan belas Mesir Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa umat Islam harus menantang interpretasi teks-teks suci yang diberikan oleh ulama abad pertengahan dan alasan itu harus diterapkan untuk menginterpretasi ulang dekrit sebelumnya. Abduh berpendapat bahwa Islam menghindari tiruan tradisi dan menunjukkan bahwa pemikiran independen merupakan prasyarat penting bagi evolusi masyarakat Muslim dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang sejati. Seperti Albert Hourani, seorang sarjana pemikiran liberal Arab menyimpulkan, “Abduh yakin bahwa negara-negara Muslim tidak bisa menjadi kuat dan makmur lagi sampai mereka memperoleh kekuatan dari Eropa, ilmu-ilmu yang merupakan produk dari aktivitas pikirannya, dan mereka dapat melakukan ini tanpa meninggalkan Islam, karena Islam mengajarkan penerimaan semua produk akal.” Mirip dengan para teolog pembebasan di dunia Kristen, Abduh menekankan bahwa Islam harus dipahami dengan benar yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan buatan manusia itu sendiri dan memastikan persamaan hak bagi semua, jika saja monopoli atas eksegesis ulama harus dihapuskan. Tidak mengherankan, Abduh dicap kafir oleh kaum tradisionalis.
Selama dua dekade terakhir, globalisasi telah berkontribusi pada pembentukan dan peningkatan aktivitas jaringan Muslim transnasional yang mendukung reformasi Syariah. Jaringan-jaringan ini secara substansial telah memajukan masyarakat sipil yang lebih inklusif, pluralistik dan bersemangat yang menolak esensialisme palsu dan identitas warisan masa lalu. Berkat sebagian jaringan ini, semakin sulit bagi kekuatan-kekuatan radikalisme untuk meminggirkan dan menekan kaum Muslim modern yang saleh dan berpikiran bebas yang mencari reformasi demi kebaikan masyarakat mereka.
Memang, sementara literalisme Islam dan sektarianisme telah menjadi dominan di banyak masyarakat, peluang baru mulai muncul bagi umat Islam yang mencari reformasi modern Syariah. Dipercaya secara luas bahwa perjuangan politik di dunia Muslim telah memecah belah para sarjana Muslim menjadi dua kubu: sekularis modern dan Islamis terbelakang. Ini adalah dikotomi palsu, karena seperti yang diketahui oleh cendekiawan Melayu Adis Duderija, blok ketiga telah muncul belakangan ini yang memajukan pemikiran kritis-progresif Muslim dan yang menolak baik perseteruan kritisisme Barat maupun fundamentalis Islam. Aliran pemikiran ini berfokus pada menafsirkan kembali ajaran-ajaran Alquran normatif yang sejalan dengan pandangan global dan dengan cara memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konteks khusus mereka.
Secara khusus, Duderija berpendapat bahwa aktivis ulama-progresif harus kritis. wacana Hegemonik Muslim pada isu-isu yang berkaitan dengan modernitas, hak asasi manusia, gender, keadilan, dan demokrasi, dan (2) mainstream sosio-politik dan hukum Barat teori, dan beberapa asumsi Pencerahan sekuler. ” Fokus mereka adalah pada pemberdayaan individu, termasuk wanita Muslim, dan pada memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi individu dalam kehidupan agama dan politik Muslim.
Para sarjana dan aktivis yang termasuk dalam kecenderungan berbasis luas ini dalam Islam kontemporer sedang mengembangkan konsep dan paradigma baru baik dalam politik domestik maupun internasional. Para penganut pemikiran Muslim progresif-kritis berbasis di negara-negara mayoritas Muslim dan minoritas Muslim. Pemikir dan aktivis ini berusaha untuk tetap setia kepada Islam dengan membebaskan Muslim modern dari bahasa, ide, konsep teoritis dan sumber tradisi Muslim abad pertengahan. Misalnya, dalam buku barunya, Penalaran dengan Tuhan - Mengembalikan Syari'ah ke Zaman Modern , UCLA Profesor Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa Syariah lebih seperti hukum umum yang berkembang daripada seperangkat aturan dan perintah yang ditetapkan. Fadl berpendapat bahwa para ahli hukum Islam awal, seperti Imam al-Syafi'i (820 H), mengubah aturan mereka untuk konteks yang berbeda:
Orientasi fundamentalis dan esensialistik kontemporer membayangkan hukum Islam menjadi sangat deterministik dan kasuistis, tetapi tentu saja ini sangat berbeda dengan epistemologi dan institusi dari tradisi hukum Islam yang mendukung keberadaan beberapa aliran pemikiran hukum yang sama ortodoks dan otoritatifnya, yang kesemuanya merupakan representasi yang valid dari kehendak ilahi.
Sejumlah pemikir progresif-kritis lainnya berpendapat yang sama terhadap tradisi Islam, para sarjana ini mulai dari Amina Wadud dan Omid Safi di Amerika Serikat hingga Farid Esack di Afrika Selatan, Hasan Hanafi di Mesir, Ali Ashgar Engineer di India, Enes Karic di Bosnia, FA Noor di Malaysia, dan almarhum Nurcholish Majid di Indonesia.
Banyak dari para pemikir ini mengakui bahwa kaum modernis Muslim pada akhirnya akan gagal menemukan penerimaan arus utama. Mereka mengamati bahwa sejak jaman modernisme, Islam tidak memajukan metodologi sistematis untuk menafsirkan Syariah, Islam telah terbukti tidak berhasil dalam menggantikan ontologi modern Islam dengan modern yang selazimnya. Sebaliknya, pemikiran Muslim modernis malah menjadi upaya kebangkitan budaya yang terpencar-pencar yang dimotivasi oleh kesulitan zaman kolonial dan gejolak sosial-politik, ekonomi, dan kulturalnya. Generasi baru reformator kritis-progresif berusaha untuk menghindari hal ini. Mereka mempertimbangkan kontribusi para sarjana era abad pertengahan dalam upaya untuk menyambungkan pemahaman antara nilai-nilai Islam dan Barat,
Sementara pendekatan untuk reformasi ini masih segar dan menjanjikan, ia belum diterjemahkan ke dalam model pemerintahan yang dapat diterapkan. Namun, seiring waktu telah membuat kontribusi intelektual yang penting untuk mengatasi tantangan kontemporer di dunia Muslim dan menyediakan sarana untuk melarikan diri dari rawa ideologis.
Perempuan Muslim berjuang setiap hari terhadap dekrit patriarkal dan norma-norma yang dibangun oleh para ulama berabad-abad silam, bahwa Islam harus berusaha untuk menegakkan keadilan. Namun, para pemikir baru menentang Islamisme ini. Amina Wadud adalah contoh seorang cendekiawan Muslim yang secara halus mendukung persamaan dan keadilan Islam. Dalam buku pertamanya, Al-Qur'an dan Wanita: Membaca kembali Naskah Suci dari Perspektif Wanita, Wadud membahas ketegangan dalam ayat-ayat Al-Quran tertentu yang berkaitan dengan keadilan dan berbagai interpretasinya. Wadud telah mengedepankan konsep Al-Qur'an yang komprehensif tentang kesetaraan gender yang berkisar dari keluarga dan masyarakat hingga seluruh umat Muslim. Dalam pandangannya, patriarki pada dasarnya tidak Islami.
Wadud pernah bertanya apakah Al-Qur'an sendiri mendukung ketidaksetaraan jender; memanfaatkan hermeneutika tauhid (kesatuan Allah), ia menetapkan bahwa itu tidak mungkin. Baginya, Tuhan berada di atas manusia, yang dilahirkan setara dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, satu orang yang memandang diri mereka lebih unggul dari yang lain, seperti dalam patriarki, seperti menyamakan diri dengan Tuhan sambil menentang prinsip tauhid. Wadud juga pernah menyoroti konsepsi Al-Quran tentang khilafah (wakil Tuhan), di mana Tuhan menciptakan insan (manusia) tanpa diskriminasi gender. Setiap manusia harus dianggap sebagai wakil Tuhan di Bumi.
Wadud juga berpendapat bahwa konsep-konsep yang lebih tinggi telah diungkapkan dalam Al Qur'an untuk menggantikan interpretasi sejarah. Misalnya, ia mengutip ayat (4: 3) memungkinkan seorang pria untuk menikahi hingga empat istri. Bagi Wadud, ayat ini harus terletak dalam konteks tertentu di mana ia diwahyukan, yaitu, dari abad ketujuh Arabia ketika poligami adalah hal yang lumrah. Dia berpendapat bahwa Quran mengajarkan, mengambil istri tambahan secara langsung bergantung pada perlakuan yang tidak diskriminatif dan adil terhadap semua istri.
Mungkin contoh paling menyentuh dari penafsiran kritis Wadud berlaku untuk ayat Al-Quran yang tampaknya menyetujui pemukulan istri (4:34). Wadud dan para sarjana lainnya menggunakan analisis linguistik untuk mengidentifikasi beberapa makna Arab klasik yang tidak lagi digunakan saat ini. Misalnya, istilah doroba telah dianggap sebagai pengesahan pemukulan, tetapi bisa juga berarti "pergi" dalam arti mendidik. Melalui ini, Wadud telah memaparkan pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan gender.
Dalam bukunya tahun 2005, Inside the Gender Jihad , Wadud menekankan pentingnya melihat Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks. Wadud menambahkan bahwa beberapa wahyu ilahi yang berkaitan dengan praktik-praktik tertentu yang umum pada abad ketujuh dibatasi oleh waktu. Salah satu contohnya adalah perbudakan, yang "dimaafkan dan diatur tetapi menjadi tidak dapat diterima di zaman modern. Singkatnya, Wadud berpendapat bahwa sementara teks-teks Islam banyak memberikan kerangka spiritual dan intelektual utama, secara literal, Islam telah memberi banyak aplikasi tetapi masih membatasi dan perlu dikontekstualisasikan lebih lanjut.
Riffat Hasan, seorang sarjana Pakistan yang berbasis di Amerika Serikat, juga telah memperdebatkan penggunaan rasionalitas dalam menangani hak-hak perempuan. Seperti yang ia katakan, “Tidak hanya Al-Qur'an yang menekankan bahwa kebenaran itu identik dalam kasus laki-laki dan perempuan, tetapi ia menegaskan, secara jelas dan konsisten, kesetaraan perempuan dengan laki-laki dan hak fundamental mereka untuk mengaktualisasikan potensi manusia dengan yang mereka bagi harus setara dengan laki-laki.” Dengan cara ini, Hasan menyatakan bahwa Al Qur'an melampaui egalitarianisme karena menampilkan pertimbangan khusus untuk perempuan dan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.
Di zaman modern, meskipun ada tekanan dari undang-undang anti-perempuan yang telah dilembagakan di bawah pakaian “Islamisasi” di beberapa negara Muslim, kaum wanita yang berpendidikan secara bertahap menyadari bahwa agama digunakan sebagai alat penindasan dan bukan sebagai jalan menuju cita-cita yang lebih besar. seperti hak dan kebebasan. Hassan berpendapat bahwa "Tuhan, yang berbicara melalui Al-Quran, dicirikan dengan keadilan, dan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran bahwa Tuhan tidak akan pernah bersalah atas 'zulm ' (ketidakadilan, tirani, penindasan, atau kesalahan)." Jadi, Al-Quran tidak dapat diperlakukan sebagai sumber ketidakadilan manusia, dan diskriminasi yang dikenakan perempuan Muslim tidak dapat dipandang sebagai keputusan Tuhan yang ditakdirkan. Tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk mengantarkan kedamaian yang hanya bisa ada dalam lingkungan yang adil.
Dalam pandangan Hassan, "teologi feminis" diperlukan dalam kerangka sistem keyakinan Islam "untuk membebaskan tidak hanya perempuan Muslim, tetapi juga laki-laki Muslim, dari struktur sosial yang tidak adil dan sistem pemikiran yang membuat hubungan teman sebaya antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin.”
Hassan bergabung dengan mereka yang berpendapat bahwa undang-undang diskriminatif yang diundangkan atas nama Islam“ tidak dapat dibalikkan hanya dengan tindakan politik, tetapi harus melalui penggunaan argumen agama yang lebih baik.” Contoh terbaru dari interpretasi modernis seperti itu adalah Maroko, di mana perempuan aktivisme telah menyebabkan revisi komprehensif hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga.
Gagasan Ghamidi yang lebih terkait dengan jihad, dia berpendapat bahwa individu, atau suatu kelompok, belum diberikan izin untuk menyatakan perang. Hanya negara yang sah dengan kekuasaan dan otoritas politik yang terorganisir yang dapat menyatakan perang. Ketika tinggal di Mekah, Muhammad Saw dan para sahabatnya tidak diizinkan untuk berperang. Tetapi setelah melakukan imigrasi ke Madinah, mereka mengorganisasi sistem politik yang memungkinkan peperangan dalam rangka membela diri.
Dalam pandangan Ghamidi, jihad sebenarnya berarti menempatkan semua upaya dan sumber daya Anda untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula, untuk berperang bagi Islam, memerangi orang yang tidak beriman, penindasan, dan ketidakadilan diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu. Para nabi dan rekan mereka hanya bisa berperang demi iman; setelah mereka, tidak ada Muslim yang memenuhi syarat untuk mengejar ini karena mereka bukan utusan Tuhan. Ghamidi juga menyatakan bahwa Quran tidak memerintahkan hukuman mati untuk murtad. Hukuman mati hanya berlaku dalam kasus pembunuhan, atau ketika harmoni sosial terganggu. Selain itu, bagi Ghamidi, orang yang tidak percaya yang melakukan perbuatan baik dan percaya kepada Tuhan akan diberi pahala pada Hari Kiamat. Hubungan antara Muslim dan non-Muslim diizinkan, dan negara-negara Muslim dapat berinteraksi dengan negara-negara non-Muslim sesuai dengan kepentingan bersama mereka.
Ada banyak yang menyerukan penolakan terhadap interpretasi jihadis yang sempit, termasuk ulama reformis Pakistan yang menarik, Tahir ul Qadri, yang menulis fatwa menentang terorisme dan pemboman bunuh diri. 48 Qadri menekankan bahwa pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap umat Islam adalah melanggar hukum dan bahwa Islam tidak memberikan sanksi tindakan terorisme terhadap non-Muslim. Karyanya menggunakan sumber-sumber tradisional dan telah membantu memajukan cakupan Syariah sebagai interpretasi yang hidup dari fatwa Islam yang berasal dari kitab suci. Singkatnya, fatwa melarang pemboman bunuh diri "tanpa alasan, dalih apapun, atau pengecualian." 49 Ketika ISIS mulai merebut wilayah secara brutal, lebih dari 120 ulama Muslim dari seluruh dunia mengeluarkan surat terbuka yang menyanggah ISIS'penafsiran Islam. 50 Namun, sudut pandang ini telah membatasi daya tarik populer di Timur Tengah dan dunia Muslim lainnya, terutama karena propaganda ISIS mengklaim bahwa itu mewakili Islam asli dan bertentangan dengan diktat Barat.
Kerendahan hati religius yang sama yang dibimbing oleh dedikasi kepada yang abadi dan dengan alasan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis kontemporer di dunia Muslim. Banyak teolog arus utama telah menunjukkan bagaimana ini mungkin terjadi. Karya-karya ulama seperti Muhammad Tahir-ul Qadri di Pakistan, Fethullah Gulen di Turki dan Habib Ali al-Jifri di Yaman memerlukan penyebaran yang lebih luas, terutama di dunia Arab dan Afrika di mana Islam penuh kekerasan sedang melaksanakan agenda mereka. Di Arab Saudi dan Teluk, suara Salman al-Awdah, yang mengkhotbahkan non-kekerasan meskipun dari mandat Salafi wahabi, perlu beresonansi dan bergabung dengan gerakan-gerakan reformis lainnya. Al-Awdah telah mengambil posisi publik bahwa suatu teokrasi tidak "Islami" dan bahwa "demokrasi terbukti lebih baik daripada otokrasi."
Mungkin satu hambatan utama untuk reformasi skala penuh adalah, bahwa dunia Muslim saat ini tidak memiliki otoritas agama pusat yang bersatu yang mampu melakukan upaya berskala besar semacam itu. Ini lebih benar untuk varian dominan Sunni Islam. Islam Syi'ah dan banyak sub-sekte memiliki sesuatu yang lebih mendekati otoritas terpusat. Sementara itu, dalam mengatasi krisis Islam Sunni tentunya akan sangat tergantung pada kemajuan masyarakat sipil dan melampaui rawa ideologis yang dihadapi oleh pemikiran agama dan politik Islam.
Al-Qaeda, ISIS dan afiliasinya telah membunuh lebih banyak Muslim daripada non-Muslim. Ini adalah pesan penting yang masih perlu diperkuat di dunia Muslim. Selain itu, pendekatan kritis akan menunjukkan betapa permusuhan populer terhadap Barat sebenarnya malah memperparah krisis dengan memicu daya tarik Islamisme dan sekaligus menghambat pemikiran alternatif tentang reformasi. Dalam hal ini, pemanggilan akal dan rasionalitas sebagai dasar kebangkitan Islam mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, pemikiran baru ini tidak dapat mencapai pengaliran arus utama sampai sekelompok massa Muslim kritis mengatasi reruntuhan ideologis yang mereka hadapi saat ini, menafsirkan ulang, dan memodernkan dekrit islam. Saat ini, ada upaya kecil tetapi penting untuk menantang dan mengembangkan alternatif terhadap Islamisme dari dalam masyarakat Muslim sendiri. Adalah kewajiban berpikir umat Islam untuk mengembalikan jalannya sejarah Muslim ke arah yang lebih positif dan damai.
Dalam beberapa tahun terakhir, pencarian alternatif untuk Islamisme telah digagalkan oleh konflik sektarian yang meluas dalam Islam, yang telah meningkatkan ketegangan dan mendorong kekerasan di seluruh dunia. Mengingat keadaan darurat ini, kebutuhan untuk mereformasi yurisprudensi Islam dan pemikiran sosial telah menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Ancaman Islamisme terhadap Muslim itu sendiri, bagaimanapun, telah diperparah oleh melemahnya pemikiran kritis dalam tradisi agama dan politik Islam. Dalam mengembangkan alternatif reformis terhadap Islamisme itu sendiri, umat Islam memang memiliki tubuh substansial dari pemikiran historis maupun kontemporer yang dapat mereka manfaatkan untuk membantu memperbaiki struktur politik dan sosial guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Krisis Hari Ini
Daya tarik Islamisme berasal dari kebangkitan modern dalam dua tendensi luas yang berjalan. Pertama, pendekatan literalis terhadap kitab suci Islam yang disebarkan oleh Salafisme modern; dan, kedua, revitalisasi ketegangan sektarian berabad-abad - terutama antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Hari ini, kebangkitan interpretasi literalis dari Syariah dan memburuknya perpecahan sektarian dalam Islam telah melahirkan siklus kekerasan abadi yang secara langsung membahayakan kehidupan Muslim di seluruh dunia.Pandangan umum yang disebarkan oleh kelompok Islamis dari semua varietas hukum Syariah “secara ilahiah sudah ditakdirkan” dan tidak dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, syariah harus dipahami secara harfiah, dan Islamis didorong oleh keyakinan mereka bahwa Syariah merupakan sistem politik dan kepercayaan yang komprehensif. Islamis harus melihat Syariah sebagai satu-satunya sumber politik dan pemerintahan yang sah; akibatnya, mereka percaya bahwa Syariah harus ditegakkan di seluruh dunia oleh negara Islam yang kuat dan luas. Dalam mencapai tujuan ini, kaum Islamis telah mengejar tujuan-tujuan politik transisional melalui berbagai cara, termasuk proselitisasi dan perjuangan bersenjata. Fokus langsung perjuangan mereka adalah menggusur elit dan kekuatan militer yang berorientasi Barat di masyarakat Muslim, pada akhirnya, mereka akan menggulingkan apa yang mereka pandang sebagai rezim musuh yang menindas yang telah menduduki masyarakat Muslim.
Asal-usul ekstremisme Islam
Asal-usul ekstremisme Islam modern dapat ditelusuri ke gerakan abad kesembilan belas di dunia Arab dan Asia Selatan yang bertujuan menghidupkan kembali Islam sebagai kekuatan politik. Pada saat itu, Islamisme bangkit sebagai tanggapan terhadap kelemahan Muslim yang tampak relatif terhadap Kerajaan Inggris dan penetrasi nilai-nilai sekuler Barat ke dalam masyarakat Muslim. Mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan revivalis ini mengkhotbahkan apa yang menjadi interpretasi mereka yang semakin radikal terhadap teks-teks suci Islam, demi memajukan tujuan politik dari kesatuan pan-Islam dan akhirnya mengadopsi hukum Syariah.Apa yang dibuktikan oleh para pembasmi abad kesembilan belas dan ahli warisnya adalah, bahwa sebagian besar aturan hukum dan striktur yang terdiri dari Syariah dikembangkan selama abad kesembilan dan kesepuluh dari Kerajaan Abbasiyah yang besar (750 H-1258 H), yakni dua abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Badan hukum tradisional ini terdiri dari pendapat hukum para ahli hukum yang menafsirkan Quran dan tradisi para nabi. Seperti semua sistem hukum dan politik buatan manusia lainnya, prinsip-prinsip dan nilai-nilai interpretasi ini tidak boleh dilihat sebagai statis tetapi sebagai dinamis dan evolusioner tergantung pada konteksnya. Akan tetapi, perlu dicatat juga bahwa pendekatan literalis terhadap Syariah pada dasarnya membekukan penafsiran yang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh sarjana Ziauddin Sardar, dominasi literalisme membuatnya dipercaya menjadi penerima pasif daripada pencari kebenaran aktif. Kenyataannya, Syariah tidak lebih dari sekumpulan prinsip, kerangka nilai, yang memberi panduan kepada masyarakat Muslim.
Pembekuan penafsiran ini telah meningkatkan Syariah secara palsu menjadi status teks ilahi. Selama berabad-abad, ini mengarah pada legitimasi - dan permintaan - sebuah literalisme yang menangguhkan agen manusia dan mengesampingkan persyaratan dunia yang terus berubah. Bersamaan dengan itu, Islam juga berbaur dengan kekuasaan negara ketika kerajaan-kerajaan Muslim berusaha melegitimasi kekuasaan mereka dengan dekrit dari ulama tradisionalis. Misalnya, ciri kode hukum sebuah konsep "kemurtadan," yang secara historis melayani untuk mencegah pemberontakan melawan negara kekaisaran. Islamis modern, baik yang terorganisir sebagai negara dalam kasus Arab Saudi, Republik Islam Iran dan Afghanistan di bawah Taliban, atau sebagai milisi dalam kasus Boko Haram di Afrika Barat, telah mengeksploitasi aspek kuno jurisprudensi tradisional islam untuk menegakkan sendiri agenda politik yang radikal.
Sepanjang sejarah Islam, para pemikir Muslim bebas mengangkat suara mereka melawan kodifikasi ketat pemikiran dan praktik Islam. Namun yang terpenting, pandangan-pandangan alternatif ini selalu menghadapi perlawanan yang kuat dan sering kali dibatalkan. Misalnya, cendekiawan dan teolog Islam Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazali (1058-1111 H) dengan keras mengkritik praktik Mu'tazilah yang menundukkan teologi Islam ke rasionalisme. Seiring waktu, peran para filsuf Muslim secara signifikan juga ikut melemahkan. Pada 1017-18 dan 1029, Khalifah Abbasiyah al-Qadir (947-1031 H) malah mengeluarkan dekrit yang dikutip secara luas yang melarang Mu'tazilitisme, dalam memadamkan perbedaan pendapat, seluruh kelompok dianiaya dan teks mereka dihancurkan. Bahkan hari ini, berabad-abad kemudian, karya-karya Ibn al-Rawandi, Ibn Rushd, dan al-Biruni - pemikir Muslim progresif dan ilmiah di zaman mereka - dilarang dari kurikulum resmi di Arab Saudi dan sebagian besar negara-negara Teluk. Sebaliknya, hanya para ulama dan sekolah yurisprudensi yang diakui resmi yang dianggap sah.
Dari berbagai mazhab pemikiran Islam, Salafisme - dan manifestasinya yang lebih kontemporer, Wahhabisme - melambangkan literalisme Salawi yang memfosil dan memperlakukan hukum buatan manusia sebagai sesuatu yang ilahi. Istilah Salafisme berasal dari al-salaf al-salih (leluhur yang saleh) maksudnya menggunakan cara Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fokus utamanya ada pada apa yang merupakan perilaku religius dan sosial Nabi. Perilaku ini disimpulkan dari Sunah (tradisi Nabi Muhammad dikompilasi dalam Hadis). Semua varian keyakinan dan praktik lainnya dianggap bid’a, atau inovasi yang tidak diinginkan.
Salafi wahabi selalu menganggap kitab suci sebagai keputusan terakhir. Sebaliknya, sekte lain dalam Islam memandang kitab suci sebagai pesan dari Tuhan yang masih membutuhkan interpretasi dan pemahaman sebelum penerapannya dalam praktik di dalam kehidupan. Para ulama Salaf mengutuk adat setempat dan praktik-praktik Muslim yang lebih mistis dari sekte-sekte seperti para Sufi, karena mereka secara sengaja merusak identitas Islam. Kutukan ini, yang dikenal sebagai takfir, adalah bagian dari doktrin radikalisme Salafi wahabi.
Pada abad kedelapan belas, Muhammad bin Abd al-Wahhab berhasil mengubah doktrin Salafi wahabi menjadi kerangka politik. Yang paling penting, perjanjiannya dengan Muhammad Ibn Saud, emir Dar'iyyah di Arabia timur laut, memberikan Wahhabisme Salafi 'kekuatan' dengan sang raja untuk pembentukan teokrasi Salafis abad kesembilan belas. Pada abad ke-20, penemuan besar minyak mempermudah komitmen Saudi untuk menyebarkan Wahhabisme ke seluruh dunia, dari Afrika Barat sampai ke Asia Tenggara. Hari ini, literalisme Salafis dan puritanisme ideologis yang didukung oleh Wahhabisme telah dianut oleh banyak Islamis, termasuk al-Qaeda dan ISIS.
Tren sejarah besar kedua yang telah melanda dunia Muslim dengan menghambat reformasi politik dan mendorong kekerasan adalah sektarianisme Sunni dan Syiah. Kebangkitan sektarianisme telah bergandengan tangan dengan dominasi literalisme Syariah. Seperti diketahui, salah satu target ideologi takfiri Salafi wahabi adalah sekte Syiah, yang menunjukkan perpecahan paling awal dalam tradisi agama. Sektarianisme modern juga didorong oleh persaingan geopolitik. Sunni Saudi Arabia dan Syiah Iran selama bertahun-tahun telah mengeksploitasi perpecahan sektarian dalam persaingan mereka untuk kepemimpinan dunia Islam. Kontes sektarian ini dimainkan setiap hari di berita utama internasional, tetapi berakar pada sejarah politik Islam.
Dalam satu abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, para pengikutnya telah membangun sebuah kerajaan yang membentang dari Eropa Spanyol ke Asia Tengah. Namun perdebatan tentang suksesi memisahkan Muslim di awal-awal kebangkitan. Kelompok dominan memilih Abu Bakr, seorang sahabat Muhamad, sebagai khalifah pertama dan menyingkirkan klaim kelompok lain yang telah mengusulkan Ali ibn Abi Thalib, sepupu Muhammad dan menantu laki-laki. Istilah Syiah berhubungan dengan shi'atu Ali, atau pengikut Ali.
Khalifah bermigrasi keluar dari Jazirah Arab dan melintasi Timur Tengah modern, pertama ke Damaskus di bawah dinasti Umayyah, dan kemudian ke Baghdad di bawah dinasti Abbasiyah. Selama berabad-abad, kekuasaan Sunni mendominasi dunia Muslim sampai dinasti Safawi yang besar di Persia yang mengadopsi Islam Syiah sebagai agama negara mereka. Orang-orang Safawi berjuang melawan khalifah Utsmaniyah untuk mendapatkan supremasi yang secara luas menetapkan garis-garis patahan geografis dan politik Timur Tengah saat ini: Syiah berada di mayoritas negara Iran, Irak, Azerbaijan, dan Bahrain; sementara itu, Sunni mendominasi di lebih dari empat puluh negara Islam dari Maroko sampai ke Indonesia.
Wahabi menilai praktik Muslim Syiah dan sistem kepercayaan mereka sebagai murtad. Ini telah diperkuat oleh perbedaan etnis antara dunia Arab (Sunni) dan Persia (Syiah). Sementara itu, retorika yang tidak manusiawi sektarian telah muncul selama berabad-abad, teknologi baru dan media sosial telah meningkatkan cakupan dan skala kritik Salafi. Islamis Sunni telah menggunakan pengaduan yang keras dan bersejarah seperti rafidha, penolak keyakinan, dan majus, Zoroaster atau crypto-Persia, untuk menggambarkan Syiah. Sementara para pemimpin Syiah dari Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, kepada para pejabat Iran secara rutin menggambarkan lawan-lawan Sunni mereka sebagai takfiri (kode untuk teroris al-Qaeda) dan Wahabi. Pada 2015, kaum fundamentalis tidak lagi harus menyusup ke masjid-masjid arus utama untuk merekrut secara diam-diam; sebagai gantinya, mereka mengklik posting blog, mereka dapat menyebarluaskan panggilan mereka untuk berjihad. Hari ini, puluhan ribu militan sektarian yang terorganisir mampu memicu konflik berskala besar di seluruh Timur Tengah.
Terlepas dari upaya banyak ulama Sunni dan Syiah, seperti Mohammad Abduh di Mesir, Mohammad Iqbal di Inggris India (modern Pakistan) dan Ali Shariati di Iran, untuk mengurangi ketegangan melalui dialog dan pemahaman, banyak ahli menyatakan keprihatinan merka, bahwa pembagian utama Islam akan menyebabkan eskalasi kekerasan. Di masa lalu, Sunni al-Qaeda dan Syiah Hizbullah mungkin tidak mendefinisikan gerakan mereka dalam istilah sektarian; sebaliknya, mereka secara tradisionalis lebih menyukai kerangka anti-imperialis, anti-Zionis dan anti-Amerika untuk menggambarkan jihad mereka dan tujuan Islamnya. Selama dekade terakhir, kedua kelompok telah bergeser dari fokus pada Barat dan Israel untuk menyerang Muslim lainnya, seperti pembunuhan al-Qaeda terhadap warga sipil Syiah di Irak dan partisipasi Hizbullah dalam perang sipil Suriah.
Hari ini, sebagai keturunan al-Qaeda, ISIS berusaha menyatukan dunia Muslim dan mengubah batas-batas geografis Timur Tengah sebelum mengubah senjatanya di Amerika Serikat dan Eropa. ISIS percaya bahwa upaya mereka yang pertama adalah harus menyingkirkan orang murtad dan Muslim "palsu", sebuah definisi yang mencakup siapa saja yang melawan mereka, bukan hanya Syiah. Muslim biasa mungkin tidak setuju dengan metode ISIS ini, dan interpretasinya tentang kekhalifahan, tetapi gagasan tentang kekhalifahan - entitas politik historis yang diatur oleh hukum dan tradisi Islam - bahkan sangat kuat di kalangan Muslim yang berpikiran lebih sekuler.
Menuju Yurisprudensi Kritis-Progresif
Korban terbesar dari kekerasan dan pergolakan sosial dan keterbelakangan yang disebabkan oleh literalisme Syiah dan pembagian sektarian adalah Muslim. Jika mereka ingin melarikan diri dari nasib mereka, sangat penting bahwa dunia Muslim memupuk para reformis. Selama berabad-abad, para reformis dan pemikir bebas semacam Mu'tazilah - secara berkala telah muncul, meskipun suara mereka sering diabaikan dan terpinggirkan.Dalam konteks Asia Selatan, barangkali pemenang terbesar pendekatan modernis untuk yurisprudensi adalah penyair dan pemikir India, Mohammed Iqbal. Menurut Iqbal, tradisional untuk inovasi hukum dalam Islam telah kalah karena ketakutan konservatif fragmentasi sosial yang diperburuk oleh rasionalisme Islam. Ketakutan ini telah menyebabkan kaum Muslim konservatif menggunakan pemahaman Syaria yang semakin sistematis dan puritan. Dengan menolak penggunaan nalar dalam menafsirkan Syariah berdasarkan konteks yang berubah, Iqbal berpendapat bahwa "massa yang tidak berpikir" akan ditinggalkan oleh para elit Muslim di "tangan-tangan intelektual" bahwa ini memaksa mereka untuk mematuhi "secara membabi buta" aturan sekolah-sekolah yang paling dominan.
Iqbal berpendapat bahwa umat Islam harus dibebaskan dari cengkeraman para teolog dan ahli hukum primitif. “Seluruh masyarakat,” tulisnya, “membutuhkan perombakan menyeluruh terhadap mentalitasnya yang sekarang agar dapat kembali merasakan keinginan dan cita-cita segar.” Menurut Iqbal, Al-Qur'an dimaksudkan untuk “membangkitkan manusia akan kesadaran yang lebih tinggi dari hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta” guna meletakkan prinsip-prinsip hukum umum dan aturan untuk perilaku manusia (khususnya, sehubungan dengan kehidupan keluarga). Karena ajaran seorang nabi berhubungan dengan "kebiasaan, cara, dan kekhasan orang-orang yang mencintainya "pendekatan terbaik untuk politik adalah memilih kelompok orang sebagai inti pusat untuk melembagakan "Syariah universal" yang berbasis konsensus.” Dengan kata lain, hukum dan praktik Islam harus mencerminkan universalitasnya dan tetap selaras dengan waktu mengedepankan prinsip pemikiran evolusi dalam Al Qur'an. Sebagai hasilnya, menurut Iqbal, “Al-Quran mengajarkan bahwa hidup adalah proses penciptaan progresif yang mengharuskan setiap generasi, dibimbing tetapi tidak terhalang oleh karya para pendahulunya, harus diizinkan untuk memecahkan masalahnya sendiri.”
Ajaran Iqbal didasarkan pada prinsip Islam ijma, atau konsensus, yang merupakan sumber utama yurisprudensi Alquran. Iqbal berpendapat bahwa secara historis prinsip konsensus ini tidak pernah mengambil bentuk kelembagaan karena itu akan menggerogoti otoritas kekaisaran khalifah. Dengan munculnya republik Muslim nasionalis dan pembentukan lembaga legislatif di negara-negara Islam, Iqbal berpendapat bahwa sudah waktunya ijma bangkit sebagai prinsip politik modern Muslim.
Selain itu, dalam pandangan dunia Iqbal, Al-Qur'an menegaskan "struktur Islam," ijtihad, atau penalaran independen, adalah cara perubahan. Ijtihad dapat dilakukan "dengan maksud untuk membentuk penilaian independen atas pertanyaan hukum" yang didasarkan pada Quran dan Hadits. Pada awalnya, penyebaran Islam dan pembentukan tatanan politik Muslim mengharuskan "pemikiran hukum sistematis" dan "dokter hukum awal," diwujudkan melalui berbagai aliran yurisprudensi Islam. Pada awal abad ke-20, bagaimanapun, Iqbal bertanya-tanya apakah dalam hukum Islam ada prospek untuk "interpretasi segar dari prinsip-prinsipnya" karena tidak inheren "stasioner dan tidak mampu melakukan pembangunan."
Selain Iqbal, sarjana Iran yang berpengaruh Ali Syariati juga menekankan bahwa Islam membutuhkan gerakan pencerahan untuk membimbing orang dan membawa dinamisme baru kepada iman. Pandangan Syariati adalah bahwa "Protestanisme Islam" diperlukan untuk kemajuan agama dan kemajuan dalam pemikiran hukumnya. Protestanisme Islam akan memungkinkan agama untuk menumpahkan faktor-faktor yang merosot yang telah melemahkan pemikirannya. Shariati berpendapat bahwa pesan-pesan agama yang ditawarkan oleh lembaga agama formal dan tradisional sudah ketinggalan zaman. Dia menyatakan bahwa hubungan antara [pendeta] dan orang-orang harus seperti hubungan antara guru dan murid - bukan antara pemimpin dan pengikut, bukan antara ikon dan peniru; orang-orang bukanlah monyet yang hanya meniru. Ide-idenya mengilhami revolusi Iran tetapi para teokrat menyesuaikan ide-idenya untuk tujuan mereka sendiri. Pesan penting Syariati tentang membebaskan Islam dari para ulama dan pemikiran-pemikiran yang ketinggalan jaman melalui nalar cukup ironis untuk dilewati dan ditumbangkan.
Pembaru abad kesembilan belas Mesir Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa umat Islam harus menantang interpretasi teks-teks suci yang diberikan oleh ulama abad pertengahan dan alasan itu harus diterapkan untuk menginterpretasi ulang dekrit sebelumnya. Abduh berpendapat bahwa Islam menghindari tiruan tradisi dan menunjukkan bahwa pemikiran independen merupakan prasyarat penting bagi evolusi masyarakat Muslim dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang sejati. Seperti Albert Hourani, seorang sarjana pemikiran liberal Arab menyimpulkan, “Abduh yakin bahwa negara-negara Muslim tidak bisa menjadi kuat dan makmur lagi sampai mereka memperoleh kekuatan dari Eropa, ilmu-ilmu yang merupakan produk dari aktivitas pikirannya, dan mereka dapat melakukan ini tanpa meninggalkan Islam, karena Islam mengajarkan penerimaan semua produk akal.” Mirip dengan para teolog pembebasan di dunia Kristen, Abduh menekankan bahwa Islam harus dipahami dengan benar yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan buatan manusia itu sendiri dan memastikan persamaan hak bagi semua, jika saja monopoli atas eksegesis ulama harus dihapuskan. Tidak mengherankan, Abduh dicap kafir oleh kaum tradisionalis.
Selama dua dekade terakhir, globalisasi telah berkontribusi pada pembentukan dan peningkatan aktivitas jaringan Muslim transnasional yang mendukung reformasi Syariah. Jaringan-jaringan ini secara substansial telah memajukan masyarakat sipil yang lebih inklusif, pluralistik dan bersemangat yang menolak esensialisme palsu dan identitas warisan masa lalu. Berkat sebagian jaringan ini, semakin sulit bagi kekuatan-kekuatan radikalisme untuk meminggirkan dan menekan kaum Muslim modern yang saleh dan berpikiran bebas yang mencari reformasi demi kebaikan masyarakat mereka.
Memang, sementara literalisme Islam dan sektarianisme telah menjadi dominan di banyak masyarakat, peluang baru mulai muncul bagi umat Islam yang mencari reformasi modern Syariah. Dipercaya secara luas bahwa perjuangan politik di dunia Muslim telah memecah belah para sarjana Muslim menjadi dua kubu: sekularis modern dan Islamis terbelakang. Ini adalah dikotomi palsu, karena seperti yang diketahui oleh cendekiawan Melayu Adis Duderija, blok ketiga telah muncul belakangan ini yang memajukan pemikiran kritis-progresif Muslim dan yang menolak baik perseteruan kritisisme Barat maupun fundamentalis Islam. Aliran pemikiran ini berfokus pada menafsirkan kembali ajaran-ajaran Alquran normatif yang sejalan dengan pandangan global dan dengan cara memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konteks khusus mereka.
Secara khusus, Duderija berpendapat bahwa aktivis ulama-progresif harus kritis. wacana Hegemonik Muslim pada isu-isu yang berkaitan dengan modernitas, hak asasi manusia, gender, keadilan, dan demokrasi, dan (2) mainstream sosio-politik dan hukum Barat teori, dan beberapa asumsi Pencerahan sekuler. ” Fokus mereka adalah pada pemberdayaan individu, termasuk wanita Muslim, dan pada memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi individu dalam kehidupan agama dan politik Muslim.
Para sarjana dan aktivis yang termasuk dalam kecenderungan berbasis luas ini dalam Islam kontemporer sedang mengembangkan konsep dan paradigma baru baik dalam politik domestik maupun internasional. Para penganut pemikiran Muslim progresif-kritis berbasis di negara-negara mayoritas Muslim dan minoritas Muslim. Pemikir dan aktivis ini berusaha untuk tetap setia kepada Islam dengan membebaskan Muslim modern dari bahasa, ide, konsep teoritis dan sumber tradisi Muslim abad pertengahan. Misalnya, dalam buku barunya, Penalaran dengan Tuhan - Mengembalikan Syari'ah ke Zaman Modern , UCLA Profesor Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa Syariah lebih seperti hukum umum yang berkembang daripada seperangkat aturan dan perintah yang ditetapkan. Fadl berpendapat bahwa para ahli hukum Islam awal, seperti Imam al-Syafi'i (820 H), mengubah aturan mereka untuk konteks yang berbeda:
Orientasi fundamentalis dan esensialistik kontemporer membayangkan hukum Islam menjadi sangat deterministik dan kasuistis, tetapi tentu saja ini sangat berbeda dengan epistemologi dan institusi dari tradisi hukum Islam yang mendukung keberadaan beberapa aliran pemikiran hukum yang sama ortodoks dan otoritatifnya, yang kesemuanya merupakan representasi yang valid dari kehendak ilahi.
Sejumlah pemikir progresif-kritis lainnya berpendapat yang sama terhadap tradisi Islam, para sarjana ini mulai dari Amina Wadud dan Omid Safi di Amerika Serikat hingga Farid Esack di Afrika Selatan, Hasan Hanafi di Mesir, Ali Ashgar Engineer di India, Enes Karic di Bosnia, FA Noor di Malaysia, dan almarhum Nurcholish Majid di Indonesia.
Banyak dari para pemikir ini mengakui bahwa kaum modernis Muslim pada akhirnya akan gagal menemukan penerimaan arus utama. Mereka mengamati bahwa sejak jaman modernisme, Islam tidak memajukan metodologi sistematis untuk menafsirkan Syariah, Islam telah terbukti tidak berhasil dalam menggantikan ontologi modern Islam dengan modern yang selazimnya. Sebaliknya, pemikiran Muslim modernis malah menjadi upaya kebangkitan budaya yang terpencar-pencar yang dimotivasi oleh kesulitan zaman kolonial dan gejolak sosial-politik, ekonomi, dan kulturalnya. Generasi baru reformator kritis-progresif berusaha untuk menghindari hal ini. Mereka mempertimbangkan kontribusi para sarjana era abad pertengahan dalam upaya untuk menyambungkan pemahaman antara nilai-nilai Islam dan Barat,
Suara Feminis
Kecenderungan kritis-progresif dalam pemikiran Islam ditandai oleh dedikasinya terhadap keadilan sosial, kesetaraan gender, non-diskriminasi agama, dan keyakinan pada martabat yang melekat pada setiap manusia sebagai pembawa ciptaan atau kholifah Allah. Prinsip-prinsip ini terdiri dari pandangan dunia dari sumber Al-Quran. Karakteristik lain yang membedakan dalam progresif kritis adalah spiritualitas dan memelihara hubungan interpersonal berdasarkan filsafat moral Sufi, yang dikenal sebagai humanisme Muslim. Kecenderungan ini juga memanfaatkan pemikiran sosial modern untuk memahami bagaimana konteks bisa berubah dan bagaimana Syariah dapat diperbarui sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu suara yang menonjol dari pemikiran ini adalah direktur Pusat Studi Islam Duke University, Omid Safi,31 Secara keseluruhan, para ahli teori progresif kritis menolak binari seperti tradisi vs modernitas, sekularisme vs agama, dan Barat vs. Islam. Bagi mereka, "kemajuan" sejarah tidak dipandang sebagai linear; para cendekiawan ini mungkin berusaha untuk belajar dari bagaimana menganalisis pengalaman-pengalaman Barat, tetapi mereka tidak menuntut penerapan model asing terhadap masyarakat Muslim. Sebaliknya, fokus mereka adalah pada realisasi kemungkinan perubahan pemikiran dalam beragama dan politik dalam konteks budaya tertentu.Sementara pendekatan untuk reformasi ini masih segar dan menjanjikan, ia belum diterjemahkan ke dalam model pemerintahan yang dapat diterapkan. Namun, seiring waktu telah membuat kontribusi intelektual yang penting untuk mengatasi tantangan kontemporer di dunia Muslim dan menyediakan sarana untuk melarikan diri dari rawa ideologis.
Perempuan Muslim berjuang setiap hari terhadap dekrit patriarkal dan norma-norma yang dibangun oleh para ulama berabad-abad silam, bahwa Islam harus berusaha untuk menegakkan keadilan. Namun, para pemikir baru menentang Islamisme ini. Amina Wadud adalah contoh seorang cendekiawan Muslim yang secara halus mendukung persamaan dan keadilan Islam. Dalam buku pertamanya, Al-Qur'an dan Wanita: Membaca kembali Naskah Suci dari Perspektif Wanita, Wadud membahas ketegangan dalam ayat-ayat Al-Quran tertentu yang berkaitan dengan keadilan dan berbagai interpretasinya. Wadud telah mengedepankan konsep Al-Qur'an yang komprehensif tentang kesetaraan gender yang berkisar dari keluarga dan masyarakat hingga seluruh umat Muslim. Dalam pandangannya, patriarki pada dasarnya tidak Islami.
Wadud pernah bertanya apakah Al-Qur'an sendiri mendukung ketidaksetaraan jender; memanfaatkan hermeneutika tauhid (kesatuan Allah), ia menetapkan bahwa itu tidak mungkin. Baginya, Tuhan berada di atas manusia, yang dilahirkan setara dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, satu orang yang memandang diri mereka lebih unggul dari yang lain, seperti dalam patriarki, seperti menyamakan diri dengan Tuhan sambil menentang prinsip tauhid. Wadud juga pernah menyoroti konsepsi Al-Quran tentang khilafah (wakil Tuhan), di mana Tuhan menciptakan insan (manusia) tanpa diskriminasi gender. Setiap manusia harus dianggap sebagai wakil Tuhan di Bumi.
Wadud juga berpendapat bahwa konsep-konsep yang lebih tinggi telah diungkapkan dalam Al Qur'an untuk menggantikan interpretasi sejarah. Misalnya, ia mengutip ayat (4: 3) memungkinkan seorang pria untuk menikahi hingga empat istri. Bagi Wadud, ayat ini harus terletak dalam konteks tertentu di mana ia diwahyukan, yaitu, dari abad ketujuh Arabia ketika poligami adalah hal yang lumrah. Dia berpendapat bahwa Quran mengajarkan, mengambil istri tambahan secara langsung bergantung pada perlakuan yang tidak diskriminatif dan adil terhadap semua istri.
Mungkin contoh paling menyentuh dari penafsiran kritis Wadud berlaku untuk ayat Al-Quran yang tampaknya menyetujui pemukulan istri (4:34). Wadud dan para sarjana lainnya menggunakan analisis linguistik untuk mengidentifikasi beberapa makna Arab klasik yang tidak lagi digunakan saat ini. Misalnya, istilah doroba telah dianggap sebagai pengesahan pemukulan, tetapi bisa juga berarti "pergi" dalam arti mendidik. Melalui ini, Wadud telah memaparkan pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan gender.
Dalam bukunya tahun 2005, Inside the Gender Jihad , Wadud menekankan pentingnya melihat Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks. Wadud menambahkan bahwa beberapa wahyu ilahi yang berkaitan dengan praktik-praktik tertentu yang umum pada abad ketujuh dibatasi oleh waktu. Salah satu contohnya adalah perbudakan, yang "dimaafkan dan diatur tetapi menjadi tidak dapat diterima di zaman modern. Singkatnya, Wadud berpendapat bahwa sementara teks-teks Islam banyak memberikan kerangka spiritual dan intelektual utama, secara literal, Islam telah memberi banyak aplikasi tetapi masih membatasi dan perlu dikontekstualisasikan lebih lanjut.
Riffat Hasan, seorang sarjana Pakistan yang berbasis di Amerika Serikat, juga telah memperdebatkan penggunaan rasionalitas dalam menangani hak-hak perempuan. Seperti yang ia katakan, “Tidak hanya Al-Qur'an yang menekankan bahwa kebenaran itu identik dalam kasus laki-laki dan perempuan, tetapi ia menegaskan, secara jelas dan konsisten, kesetaraan perempuan dengan laki-laki dan hak fundamental mereka untuk mengaktualisasikan potensi manusia dengan yang mereka bagi harus setara dengan laki-laki.” Dengan cara ini, Hasan menyatakan bahwa Al Qur'an melampaui egalitarianisme karena menampilkan pertimbangan khusus untuk perempuan dan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.
Di zaman modern, meskipun ada tekanan dari undang-undang anti-perempuan yang telah dilembagakan di bawah pakaian “Islamisasi” di beberapa negara Muslim, kaum wanita yang berpendidikan secara bertahap menyadari bahwa agama digunakan sebagai alat penindasan dan bukan sebagai jalan menuju cita-cita yang lebih besar. seperti hak dan kebebasan. Hassan berpendapat bahwa "Tuhan, yang berbicara melalui Al-Quran, dicirikan dengan keadilan, dan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran bahwa Tuhan tidak akan pernah bersalah atas 'zulm ' (ketidakadilan, tirani, penindasan, atau kesalahan)." Jadi, Al-Quran tidak dapat diperlakukan sebagai sumber ketidakadilan manusia, dan diskriminasi yang dikenakan perempuan Muslim tidak dapat dipandang sebagai keputusan Tuhan yang ditakdirkan. Tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk mengantarkan kedamaian yang hanya bisa ada dalam lingkungan yang adil.
Dalam pandangan Hassan, "teologi feminis" diperlukan dalam kerangka sistem keyakinan Islam "untuk membebaskan tidak hanya perempuan Muslim, tetapi juga laki-laki Muslim, dari struktur sosial yang tidak adil dan sistem pemikiran yang membuat hubungan teman sebaya antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin.”
Hassan bergabung dengan mereka yang berpendapat bahwa undang-undang diskriminatif yang diundangkan atas nama Islam“ tidak dapat dibalikkan hanya dengan tindakan politik, tetapi harus melalui penggunaan argumen agama yang lebih baik.” Contoh terbaru dari interpretasi modernis seperti itu adalah Maroko, di mana perempuan aktivisme telah menyebabkan revisi komprehensif hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga.
Menantang Jihadisme
Pakar modern Pakistan, Javed Ahmad Ghamidi berpendapat bahwa jalan utama untuk ijtihad telah terbuka. Adalah tugas para ulama untuk melakukan ijtihad dan mengeksplorasi kembali makna-makna baru dari ayat-ayat Al-Quran sesuai jaman yang berubah. Hal ini sejalan dengan pandangan Iqbal bahwa revisi opini lama telah membuka pandangan baru tentang kemajuan sepanjang sejarah. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para ahli hukum sebelumnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis perlu ditinjau kembali oleh para ahli hukum modern yang menulis ulang hukum-hukum Muslim berdasarkan prinsip-prinsip agama yang sejalan dengan dunia modern.Gagasan Ghamidi yang lebih terkait dengan jihad, dia berpendapat bahwa individu, atau suatu kelompok, belum diberikan izin untuk menyatakan perang. Hanya negara yang sah dengan kekuasaan dan otoritas politik yang terorganisir yang dapat menyatakan perang. Ketika tinggal di Mekah, Muhammad Saw dan para sahabatnya tidak diizinkan untuk berperang. Tetapi setelah melakukan imigrasi ke Madinah, mereka mengorganisasi sistem politik yang memungkinkan peperangan dalam rangka membela diri.
Dalam pandangan Ghamidi, jihad sebenarnya berarti menempatkan semua upaya dan sumber daya Anda untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula, untuk berperang bagi Islam, memerangi orang yang tidak beriman, penindasan, dan ketidakadilan diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu. Para nabi dan rekan mereka hanya bisa berperang demi iman; setelah mereka, tidak ada Muslim yang memenuhi syarat untuk mengejar ini karena mereka bukan utusan Tuhan. Ghamidi juga menyatakan bahwa Quran tidak memerintahkan hukuman mati untuk murtad. Hukuman mati hanya berlaku dalam kasus pembunuhan, atau ketika harmoni sosial terganggu. Selain itu, bagi Ghamidi, orang yang tidak percaya yang melakukan perbuatan baik dan percaya kepada Tuhan akan diberi pahala pada Hari Kiamat. Hubungan antara Muslim dan non-Muslim diizinkan, dan negara-negara Muslim dapat berinteraksi dengan negara-negara non-Muslim sesuai dengan kepentingan bersama mereka.
Ada banyak yang menyerukan penolakan terhadap interpretasi jihadis yang sempit, termasuk ulama reformis Pakistan yang menarik, Tahir ul Qadri, yang menulis fatwa menentang terorisme dan pemboman bunuh diri. 48 Qadri menekankan bahwa pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap umat Islam adalah melanggar hukum dan bahwa Islam tidak memberikan sanksi tindakan terorisme terhadap non-Muslim. Karyanya menggunakan sumber-sumber tradisional dan telah membantu memajukan cakupan Syariah sebagai interpretasi yang hidup dari fatwa Islam yang berasal dari kitab suci. Singkatnya, fatwa melarang pemboman bunuh diri "tanpa alasan, dalih apapun, atau pengecualian." 49 Ketika ISIS mulai merebut wilayah secara brutal, lebih dari 120 ulama Muslim dari seluruh dunia mengeluarkan surat terbuka yang menyanggah ISIS'penafsiran Islam. 50 Namun, sudut pandang ini telah membatasi daya tarik populer di Timur Tengah dan dunia Muslim lainnya, terutama karena propaganda ISIS mengklaim bahwa itu mewakili Islam asli dan bertentangan dengan diktat Barat.
Apakah Islam Kemungkinan Bereformasi?
Dalam esai baru-baru ini, penulis Turki Mustafa Akyol mencatat contoh filsuf Inggris John Locke, yang ide-idenya membawa liberalisme ke Kristen. Locke tidak menyerang agama dan mengambil kasusnya untuk kebebasan politik dan agama dari “baik alasan maupun dari Alkitab.” Akyol berpendapat, mengutip teolog almarhum abad ketujuh yang disebut Murjites, atau penunda, yang menerapkan alasan. Mereka menafsirkan iman pada saat perpecahan yang mendalam di tengah-tengah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang disebut orang-orang Khariji, atau orang-orang yang tidak setuju, yang memandang Muslim lainnya sebagai murtad. Murjites berpendapat bahwa tidak ada “Muslim memiliki hak untuk menghakimi orang lain atas masalah iman; hanya Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi. Dengan demikian, mereka beralasan, semua perselisihan doktrinal harus ditunda ke akhirat, untuk diselesaikan oleh Allah.”Kerendahan hati religius yang sama yang dibimbing oleh dedikasi kepada yang abadi dan dengan alasan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis kontemporer di dunia Muslim. Banyak teolog arus utama telah menunjukkan bagaimana ini mungkin terjadi. Karya-karya ulama seperti Muhammad Tahir-ul Qadri di Pakistan, Fethullah Gulen di Turki dan Habib Ali al-Jifri di Yaman memerlukan penyebaran yang lebih luas, terutama di dunia Arab dan Afrika di mana Islam penuh kekerasan sedang melaksanakan agenda mereka. Di Arab Saudi dan Teluk, suara Salman al-Awdah, yang mengkhotbahkan non-kekerasan meskipun dari mandat Salafi wahabi, perlu beresonansi dan bergabung dengan gerakan-gerakan reformis lainnya. Al-Awdah telah mengambil posisi publik bahwa suatu teokrasi tidak "Islami" dan bahwa "demokrasi terbukti lebih baik daripada otokrasi."
Mungkin satu hambatan utama untuk reformasi skala penuh adalah, bahwa dunia Muslim saat ini tidak memiliki otoritas agama pusat yang bersatu yang mampu melakukan upaya berskala besar semacam itu. Ini lebih benar untuk varian dominan Sunni Islam. Islam Syi'ah dan banyak sub-sekte memiliki sesuatu yang lebih mendekati otoritas terpusat. Sementara itu, dalam mengatasi krisis Islam Sunni tentunya akan sangat tergantung pada kemajuan masyarakat sipil dan melampaui rawa ideologis yang dihadapi oleh pemikiran agama dan politik Islam.
Al-Qaeda, ISIS dan afiliasinya telah membunuh lebih banyak Muslim daripada non-Muslim. Ini adalah pesan penting yang masih perlu diperkuat di dunia Muslim. Selain itu, pendekatan kritis akan menunjukkan betapa permusuhan populer terhadap Barat sebenarnya malah memperparah krisis dengan memicu daya tarik Islamisme dan sekaligus menghambat pemikiran alternatif tentang reformasi. Dalam hal ini, pemanggilan akal dan rasionalitas sebagai dasar kebangkitan Islam mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, pemikiran baru ini tidak dapat mencapai pengaliran arus utama sampai sekelompok massa Muslim kritis mengatasi reruntuhan ideologis yang mereka hadapi saat ini, menafsirkan ulang, dan memodernkan dekrit islam. Saat ini, ada upaya kecil tetapi penting untuk menantang dan mengembangkan alternatif terhadap Islamisme dari dalam masyarakat Muslim sendiri. Adalah kewajiban berpikir umat Islam untuk mengembalikan jalannya sejarah Muslim ke arah yang lebih positif dan damai.
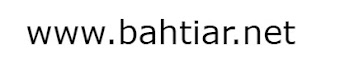











0 Comments