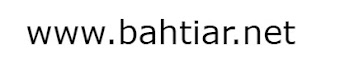Globalnya istilah taqlid dapat diterapkan dalam segala bidang meski bukan doktrin problematika agama. Seperti orang sakit yang mengikuti pendapat dokter untuk mimum obat. Namun, pada kenyataannya istilah taqlid lebih akrab diartikan mengikuti pendapat seorang ulama (mujtahid) dalam permasalahan agama tanpa harus mengetahui dasar (dalil) dan metodologi penggalian hukumnya (wajhu al-dilalah).
Dalam bertaqlid, seseorang tidak harus mengucapkan atau berniat taqlid kepada seorang imam. Setiap kali melakukan sesuatu dan terbersit dalam hatinya bahwa apa yang ia lakukan sesuai dengan pendapat seorang ulama, maka ia dikategorikan orang yang taqlid kepada ulama tersebut.
Hukum Taqlid
Umumnya, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni orang pandai dan bodoh. Yang dimaksud orang pandai dalam diskursus pemahaman ijtihad dan taqlid adalah orang yang memiliki kemampuan menggali hukum dari al-Qur'an dan al-hadits (mujtahid). Sedangkan orang-orang bodoh (muqallid, awam) adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut.Hukum taqlid dalam problematika furu' ad-din (cabang agama) adalah wajib bagi selain para mujtahid, baik mereka yang masih awam atau yang sudah alim tapi belum mencapai derajat ijtihad. Sebab jika tidak taqlid, mereka tidak bisa mengetahui hukum agama sehingga tidak bisa melaksanakannya. Sedangkan dalam diskursus usul ad-din (tauhid; keyakinan), hukum taqlid menjadi obyek perselisihan para ulama.
Dalil kewajiban taqlid dijelaskan dalam firman Allah swt yang berbunyi:
"Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui." (QS. Al-Anbiya’; 7)
Sebagian pendapat berkomentar bahwa ayat di atas bisa dijadikan dalil kewajiban taqlid bagi orang Islam dalam hukum-hukum syari’at. Sebab ayat di atas diturunkan guna menyikapi orang-orang musyrik yang mendusatakan diutusnya Rasulullah saw. Mereka memprediksikan bahwa Allah tidak akan mengutus seorang Rasul dari jenis manusia, mereka mengatakan: "Seandainya Tuhan kami menghendaki seorang utusan maka niscaya Ia akan menurunkan malaikat."
Memang benar esensi asbab an-nuzul (sebab diturunkannya) ayat di atas guna menyikapi prediksi orang-orang musyrik. Namun dalam kaidah ushul fiqh, dikatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dan menjadi titik tekan dalam sebuah ayat adalah keumuman (universal) lafadz ayat, bukan diprioritaskan pada latar belakang turunnya ayat. Kaidah tersebut berbunyi:
الْعِبْرَةُ بـِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ
"Yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafadz bukan sebab diturunkannya ayat."
Dengan demikian ayat di atas sebenarnya mengandung perintah kepada orang-orang muslim yang tidak memiliki pengetahuan terhadap masalah agama agar bertanya dan mengikuti pendapat orang-orang pandai di antara mereka.
Secara tekstual, ayat di atas memang berisi perintah untuk bertanya kepada orang-orang pandai mengenai dalil-dalil yang mendasari terciptanya hukum. Tidak ada informasi yang memerintahkan taqlid, sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan tendensi bagi kewajiban taqlid. Namun sekali lagi pemahaman di atas kurang tepat, sebab jika diperhatikan lebih teliti, perintah dalam ayat tersebut termasuk perintah yang mutlak dan umum. Tidak ditemukan kekhususan perintah bertanya tentang dalil atau yang lain. Sehingga ayat tersebut bisa saja menjadi dalil kewajiban taqlid, pemahaman ayat di atas didukung pula oleh redaksi ayat;
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar, dan mereka meyakini ayat-ayat kami." (QS. As-Sajdah; 24)
Abu As-Su’ud berkomentar, substansi ayat di atas menjelaskan tentang para imam yang memberi petunjuk kepada umat tentang hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur`an. Dengan demikian wajib bagi umat untuk mengikuti petunjuk yang mereka berikan.
Ditambah dengan pemahaman firman Allah swt yang berbunyi;
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa’; 59)
Redaksi kata ulil amri dalam ayat di atas memancing kontradiksi ideologi ulama dalam segi pentafsirannya. Kitab al-Khozin menyebutkan, Ibnu Abbas dan Jabir pernah berkomentar bahwa, arti kata ulil amri adalah para fuqaha’ dan ulama’ yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Sehingga ayat di atas dipahami bahwa orang islam wajib taat kepada apa yang diajarkan oleh para ulama dan fuqaha. Pendapat ini disokong oleh al-Hasan, ad-Dlahak dan Mujahid.
Ayat lain menyebutkan :
"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan ulil Amri)." (QS. An-Nisa’; 83)
Imam ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan beberapa point. Pertama, dalam Islam terdapat hukum yang tidak bisa diketahui jika mengandalkan nash (al-Quran dan al-Hadits) namun dapat diketahui dengan istinbath (penggalian hukum). Kedua, istinbath termasuk hujjah. Ketiga, orang awam wajib taqlid kepada ulama’ mengenai ketentuan hukum persoalan yang terjadi.
Keberadaan taqlid sebagai kewajiban dapat dipertanggung jawabkan secara logika. Sebagaimana diketahui, setiap muslim mendapat tuntutan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan agama. Sementera tidak mungkin bagi seseorang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang ia sendiri tidak tahu akan perintah dan larangan tersebut.
Namun jika setiap muslim dituntut untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur`an dan al-hadits, tentu mereka merasa kewalahan lantaran bahasa sastra al-Quran yang begitu tinggi dan kemampuan serta kesibukan mereka yang berbeda-beda. Logikanya, kemampuan presiden dalam mengatur negara tentu jauh berbeda dengan seorang penggembala kambing, kemampuan dokter dalam mengobati penyakit tentunya akan berbeda jauh dengan seorang petani. Begitu juga kemampuan para mujtahid dalam menggali hukum dari al-Qur`an dan hadits yang jauh lebih tinggi ketimbang para muqallid.
Oleh karenanya, orang-orang yang belum atau tidak memiliki kemampuan ijtihad diperbolehkan bahkan wajib taqlid kepada mereka yang lebih pandai. Yakni mereka yang memiliki kemampuan menggali hukum.
Secara tegas Al-Quran mempublikasikan agar sebagian muslim -bukan semuanya- mau tidak mau harus menekuni ilmu agama agar disampaikan kepada mereka yang belum tahu. Allah swt berfirman:
"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap komunitas di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At- Taubah; 122)
Kewajiban taqlid ini ironisnya banyak disangkal oleh komunitas muslim yang seenak udel sendiri mengatasnamakan perkataan para imam mujtahid yang melarang taqlid. Mereka mereduksi komentar imam-imam madzhab sebagaimana berikut:
Imam Malik berkata: "Pendapat setiap orang tidak dapat diterima kecuali Rasulullah saw."
Imam Abu Hanifah berkata: "Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk menfatwakan pendapatku". Setiap kali memberikan fatwa kepada seseorang Imam Abu Hanifah selalu mengatakan: "Ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat yang terbaik menurutku. Maka barang siapa dapat memberikan fatwa yang lebih baik, itulah yang benar baginya."
Imam Syafi’i berkata: "Setiap hadits shahih adalah madzhabku." Beliau juga pernah berkata: "Ketika kalian melihat pendapatku tidak sesuai dengan sabda Rasulullah saw maka gunakanlah sabda Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku." Saat imam al-Muzani bertaqlid kepada Imam Syafi'i dalam suatu permasalahan agama, Imam Syafi'i berkata kepadanya: "Wahai Abi Ibrahim (al-Muzany) janganlah kamu taqlid kepadaku."
Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata: "Kalian jangan taqlid kepadaku, Imam Malik, Imam al-Auza'i, Imam an-Nakha’i dan lainnya. Namun ambillah hukum-hukum dari mana mereka mengambilnya."
Berbagai komentar para imam madzhab di atas memang benar adanya. Namun tidak serta merta bisa digunakan sebagai hujjah melarang taqlid. Sebab larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan berijtihad seperti imam al-Muzani dan orang-orang yang setingkat dengannya. Bukan orang-orang macam kita yang tidak mampu menelaah dan menggali hukum dari al-Qur`an dan al-Hadits.
Syarat-Syarat Taqlid
Ada beberapa variabel syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam bertaqlid. di antaranya:Pertama, orang yang taqlid (muqallid) harus mengetahui syarat dan kewajiban yang telah ditentukan oleh muqallad (orang yang diikuti) setidaknya dalam satu paket permasalahan (qadliyah) yang dijadikan obyek taqlid. Seperti masalah wudlu`, shalat, puasa, dll.
Contohnya, seseorang taqlid kepada imam malik dalam hal tidak batalnya wudlu disebabkan bersentuhan kulit dengan lawan jenis harus tahu secara menyeluruh segala hal yang ditetapkan oleh imam malik dalam masalah wudlu`. Seperti wajibnya mengusap seluruh bagian kepala dengan merata, menggosok-gosok anggota tubuh saat dibasuh (dalku), dan wajibnya muwalah (terus-menerus; tidak memisah antara basuhan anggota tubuh dengan waktu yang lama).
Seseorang yang bertaqlid kepada imam syafi’i dalam problematika tidak wajib mengusap kepala secara merata saat berwudlu, harus mengetahui ketetapan madzhab Syafi’i bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis merupakan gesekan problematika yang bisa membatalkan wudlu.
Kedua, taqlid tidak boleh dilakukan dalam persoalan yang sudah terjadi (taqlid ba’da al-‘amal) kecuali memenuhi beberapa syarat:
1. Tidak meyakini batalnya amal saat ia melakukannya,
2. Imam yang menjadi muqalladnya adalah imam yang menyetujui keabsahan taqlid ba'da al-'amal.
Contoh, seseorang yang memegang alat kelamin lalu melaksanakan shalat karena lupa atau tidak mengetahui hukum konsekwensi memegang alat kelamin, sementara ketidaktahuannya termasuk kebodohan yang dapat ditolerir (jahl ma'dzur). Maka dia diperbolehkan taqlid kepada Imam Abu Hanifah guna menggugurkan kewajiban qadla’.
Ketiga, muqallid tidak boleh seenaknya mengambil hal-hal yang mudah saja, karena akan menyebabkan ia terbebas dari beban hukum. Contoh, saat seseorang tidak menemukan air dan debu untuk bersuci ketika waktu shalat hampir habis. Ia hanya menemukan sebuah batu yang suci. Ia tidak bertayammum dengan batu itu karena satu alasan taqlid kepada Imam Syafi'i yang tidak membolehkan tayammum dengan batu. Namun ia juga tidak mengqadla'i shalat dengan alasan taqlid kepada Imam Malik yang berpendapat tidak wajib qadla bagi orang yang tidak menemukan air, debu, atau batu yang dapat dipergunakan untuk bersuci.
Keempat, muqallad (orang yang diikuti) haruslah seorang mujtahid, meski kapasitasnya sekedar mujtahid fatwa seperti Imam ar-Rafi’i, Imam an-Nawawi, Imam ar-Romli dan Imam Ibnu Hajar. Selama tidak ada asumtif bahwa pendapat imam-imam tersebut diprediksi sangat lemah. Begitu pula tidak diperbolehkan taqlid kepada seorang imam dalam pendapat yang telah dicabut kembali, selama tidak ada ulama’ pengikut madzhabnya yang mendukung pendapat tersebut berdasarkan dalil yang ia kaji dari kaidah-kaidah dalam madzhab yang ia ikuti.
Kelima, tidak talfiq, dalam arti tidak mencampuradukkan antara dua pendapat atau lebih dalam satu qodliyah (paket permasalahan) yang dapat memunculkan satu bentuk amal yang tidak sah menurut kedua belah pihak yang ia ikuti. Contoh, dalam sub syarat ketiga, seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala karena taqlid kepada Imam Syafi’i. Kemudian ia bersentuhan kulit dengan lawan jenis dan melaksanakan shalat tanpa berwudlu lagi dengan alasan taqlid kepada Imam Malik dalam hal tidak batalnya wudlu sebab bersentuhan kulit dengan lawan jenis. yang demikian ini tidak diperbolehkan karena shalat yang ia lakukan menjadi batal menurut Imam Malik maupun menurut Imam Syafi’i. Menurut Imam Malik karena wudlunya tidak sah dengan hanya mengusap sebagian kepala saja. Sedangkan menurut Imam Syafi’i karena wudlunya telah batal sebab bersentuhan kulit dengan lawan jenis.
Tanggapan-Tanggapan
Tanggapan pertama tentang ayat:
”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. al-Isra`; 36)
Sebagian ulama berkomentar bahwa ayat di atas diasumsikan sebagai larangan untuk bertaqlid, sebab taqlid diartikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya.
Asumsi tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab, jika ayat di atas menunjukkan larangan taqlid, tentu ayat di atas dipahami pula sebagai petunjuk larangan berijtihad. Karena esensi ijtihad adalah berusaha menghasilkan sebuah praduga (dhann) terhadap konstruksi hukum. Oleh karena itu, maksud dari kata al-'ilm dalam ayat di atas mencakup kualitas pengetahuan secara yakin (al-'ilm) dan pengetahuan yang bersifat praduga (dhann).
Meski dalam sebagian firman Allah swt. Praduga dianggap suatu tindakan yang tercela, namun sebenarnya ada pula konstruksi dhan yang terpuji, salah satunya adalah dhann dalam ijtihad. Allah berfirman;
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan pra-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari pra-sangka itu dosa." (QS. Al-Hujurat; 12)
Membaca ayat di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya terdapat prasangka (dhan) yang bukan perbuatan dosa/tercela. Terbukti Allah menggunakan bahasa ba'dla al-dhann (sebagian pransangka).
Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi;
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ
"Aku (Allah) sesuai prasangka hamba-Ku pada-Ku. Karena itu, berprasangkalah apa yang ia kehendaki." (HR. Bukhori)
Andaikan semua prasangka itu tercela, niscaya hukum-hukum agama akan terkesampingkan. Sebab, kebanyakan konsep hukum-hukum syari'at muncul dari kapasitas dhan.
Abi al-Fadhl bin Abdis Syakur, Op.Cit., (Surabaya: al-Hidayah), hlm.72 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang mencela dhan sebenarnya diarahkan pada dhan yang tidak memiliki dasar yang jelas dan dalil yang kuat.
Tanggapan kedua tentang ayat:
وَإِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا إِلىٰ ما أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسولِ قالوا حَسبُنا ما وَجَدنا عَلَيهِ آباءَنا ۚ أَوَلَو كانَ آباؤُهُم لا يَعلَمونَ شَيئًا وَلا يَهتَدونَ
”Apabila dikatakan kepada mereka,"Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”. (Al-Maidah; 104)
Berbagai komunitas menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk melarang taqlid, sebab dalam ayat di atas dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti pendapat nenek moyang mereka dicela dan dicacimaki oleh Allah swt.
Enyahkan ideologi ambivalensi tersebut sebab substansi ayat yang dimaksud nenek moyang adalah orang-orang kafir yang tidak mengetahui agama dan petunjuk dari Allah swt, bukan para mujtahid islam yang notabane-nya manusia berpengetahuan agama.
Dalam bidang hadits, riwayat Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw disebut dengan silsilah adz-dzahab yang merupakan rentetan mata rantai hadits yang terkuat.